Kupikir pilihan benar untuk naik ke taksinya. Pilihan tepat untuk membiarkannya membawaku ke sini. Sekarang pun aku sudah yakin. Tidak perlu lagi aku diam saat penderitaan melewatiku. Yang harus kulakukan hanyalah berlari melewatinya. - Karya Risty Gyro, Sutradara dan Penulis Teater Yupa Unmul -
IDENESIA.CO - 9 Maret 2019, sore hari/
Harus kuakui, ini bukan kali pertama aku merasa benci pada keadaanku. Bukan kali pertama, aku menghabiskan waktuku dengan sia-sia. Kalau aku masih punya tenaga, aku pasti sudah menangis sedari tadi. Namun, emosi yang akan kutumpahkan hanya akan membuatku semakin lelah.
Aku berusaha mengalihkan perasaan kesalku dengan membaca The Adventures of Sherlock Holmes, tapi kemudian yang kudapat hanya pusing di sebelah kanan kepalaku. Mungkin aku bisa menjerit dan memaki—tidak jadilah, nikmati saja keheningan ini. Aku ingin menyalahkan cuaca hari ini.

Aku mengambil ponselku di saku baju yang kukenakan. Menatap miris pada layar ponselku, selama 3 jam 28 menit aku duduk di halte itu. Dibandingkan kemarin, sepertinya hari ini aku menunggu sedikit lebih lama. Seingatku, kemarin, aku menunggu sekitar 3 jam 14 menit.
Baiklah, kusadari semakin hari semakin panjang durasi waktu yang kubutuhkan untuk menunggu. Bisa saja sih, aku menumpang pada teman-teman—ah, aku lupa, mereka terlalu sibuk dengan kegiatan-kegitan personal mereka. Atau bisa saja sih, aku naik angkutan umum—tidak, deh, aku benci suasana pengapnya. Jalan kaki? Jangan paksa aku melakukannya. Aku terlalu lelah, bahkan untuk menggerakkan kakiku.
Ditambah lagi, terjebak di tengah kemacetan kota ini. Bahkan, dibandingkan terjebak seperti ini, aku memilih untuk tersesat di hutan rimba saja. Sore yang seharusnya kunikmati dengan indah, masih kuhabiskan dengan terjebak dalam baju seragamku.
Aku mungkin saja menahan emosiku, tapi tubuhku tidak bisa. Aku yakin sekali, tubuhku ini sudah mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Bahkan, ketiakku sudah menangis duluan. Perutku pun sudah merengek. Kakiku sudah tertidur dan otakku sudah mengantuk.
Kusenderkan kepalaku ke jendela mobil. Merasakan rambatan terik matahari dibidangnya. Mataku menjelajahi setiap jengkal kehidupan di jalan sore itu, kebiasaan yang kulakukan akhir-akhir ini. Membayangkan bagaimana kalau aku berada diluar sana, bukan didalam mobil yang suhunya sengaja diatur sedingin mungkin.
Bagaimana kalau aku yang jadi model di reklame iklan shampo itu? Bagaimana kalau aku hidup di dalam videotron disana itu? Bagaimana kalau aku yang menjajakan makanan kecil di seberang jalan itu? Bagaimana kalau aku yang membersihkan jendela mobil di depan itu? Bagaimana kalau aku yang berada di atas motor bersama seorang ibu muda itu? Bagaimana sih hidup di jalan itu? Apa mereka juga seperti aku?
“Ayah, berapa lama aku harus menunggu lagi, besok?” tanyaku lemah, sebisa mungkin tidak terdengar sarkastik.
Ayahku tertawa. Aku tidak mengerti selera humornya. Sungguh. “Tidak tau, apa kau ada kegiatan sampai sore lagi?”
Masih dengan bersender, membaca plang toko diseberang jalan, aku menggeleng. “Tidak tau, aku belum cek agendaku.” Ya, aku menyusun agendaku sendiri—kalau lagi niat aja sih. Kebetulan sekali, aku banyak waktu luang—sembari menunggu, sesekali aku mencoba menyusun agendaku selama satu bulan kedepan—di halte, tempat biasa aku frustasi sendiri.
Ayah tertawa lagi, “Ayah juga, nak. Kita lihat besok saja.”
Aku tidak menyahut. Tidak juga mengangguk. Hanya diam. Menikmati deru kendaraan yang ingin lekas kembali ke rumah. Bahkan, mobil kami ikut menggeram bersama deruan itu. Lampu merah didepan itu pun, akhirnya, berkedip dan berubah warna menjadi hijau. Tahu maksudku, ‘kan?
Mobil dipacu Ayah membelah jalanan kota dengan pelan. Karena, kalau terlalu cepat, nanti bisa menabrak mobil hitam didepan kami atau mungkin saja menyerempet trotoar dan menyenggol pengamen kecil berbaju hijau muda didepan sana.
Kepalaku terantuk-antuk mengenai kaca jendela mobil, sekali lagi mengamati kendaraan-kendaraan yang berdesakan di jalan kota, sore ini. Membaca hampir semua plat kendaraan yang terlewati. Tidak juga melewatkan tulisan-tulisan aneh atau dekorasi nyentrik yang tertempel di kaca jendela mobil lain. Kebiasaan lain yang mulai muncul.
Sayangnya, kini semua itu tidak lagi bermakna, berbeda dengan mata bocahku dulu. Mata yang sama, manusia yang sama, tapi pandangan yang sama sekali lain. Keluarga yang berbeda.
Seperti siang dan malam, di bumi yang sama tetapi dengan langit yang berbeda. Di rumah yang sama tetapi dengan keluarga yang berbeda. Tidak juga, sih. Bagaimana, ya, pokoknya begitu, deh. Ada saat tatkala kata terasa sia-sia.
Kami berhenti lagi. Aku menghela nafas, tidak tau sudah berapa kali aku melakukannya. Tidak tau sudah berapa lampu lalu lintas yang mencegat jalan mobil kami.
Sekalipun sulit, tapi pikiranku berusaha keras untuk kembali. Kembali mengingat masa bocahku, bermain bebas di halaman belakang yang luas dengan senyum yang terus mengembang. Dulu, aku juga tidak pernah kesepian. Selalu saja ada Bunda yang menemani.
Hidup ternyata lucu, seringku tertawa-tawa karenanya. Bukan maksudku menertawakan takdir dan hal semacamnya. Aku percaya akan takdir yang sudah ditorehkan di atas kertas kekekalan. Tapi kemudian pikiranku mensinyalir sesuatu.
Ada jejak-jejak keresahan yang tidak pernah terungkap. Mengapa aku selalu sedih dan lelah sekali? Mengapa kebahagian pergi dari hidupku? Mengapa aku harus menyembunyikan jati diriku? Mengapa Bunda meninggalkanku? Mengapa harus aku yang mengalaminya? Mengapa harus lembar kekekalanku yang ditulis takdir menyedihkan macam ini?
Takdir menyedihkan mana lagi yang kau dustai, jika aku katakan aku pernah merasa sangat bahagia—merasa hidupku begitu sempurna—tapi, justru, pusat kebahagianku malah mengecewakanku dan meninggalkanku? Bertahun-tahun lewat sudah, dan aku tetap tidak punya jawaban atas itu semua. Dan dari sanalah kebiasaan itu muncul. Membisu di dalam mobil, membaca semua tulisan yang terlewati, memulai percakapan pada diriku sendiri.
Aku sudah kehilangan pusat kenyamananku—tempat kuberbagi cerita kala masih bocah. Lalu, kemana lagi aku harus bercerita selain kepada diriku sendiri. Silahkan, anggap aku abnormal, aku tidak peduli.
“Marista,” panggil Ayah, aku menoleh malas padanya. Jujur saja, aku juga malas untuk menanggapinya.
“Ayah baru ingat,” ucapnya lagi sambil mengetuk-ngetuk kemudi mobil, “Malam ini, ayah harus lembur. Jadi, Ayah hanya akan antarkan kau pulang. Terus, kembali lagi ke kantor,” Ayah bahkan tidak menatapku ketika ia bicara. Apa aku juga harus menjawab pernyataannya itu?
“Aku mengerti, Yah,” akhirnya aku hanya mengatakan itu. Lalu, kembali ke perjalanan menembus imajiku. Kembali kekeheningan.
Semenjak kehilangan pusat kenyamananku, aku senang menyimak keheningan, daripada harus merongrong minta perhatian. Aku bukan gadis belasan tahun yang aktif dan ceria. Aku sudah membuang sifat itu dari tumpukan dokumen usang di laci kepribadianku.
Rasa sukaku pada keheningan, membuatku jarang membuat masalah, membuatku menjadi murid yang baik. Namun, keheningan memolesku menjadi sosok teman yang tidak menyenangkan. Well, daripada menanggapi gosip murahan tentang anak penjaga kantin yang ganteng tapi tidak bersekolah itu, lebih baik kunikmati alunan musik klasik dari ponselku.
Aku tidak suka menimpali hal-hal yang tidak kuketahui kebenarannya. Kalau sesekali aku menanggapi sesuatu, itu artinya aku dalam suasana hati yang sedang bagus. Sayang sekali, suasana hatiku jarang baik. Lebih baik diam, daripada kulontarkan kata-kata yang menyakitkan.
Terkadang, Ayah bertanya tentang teman-temanku. Jujur saja, aku sudah lama tidak menyukai proses pertemanan. Aku tidak suka saat mereka berniat mengunjungi rumahku. Kalau situasinya sama seperti aku bocah dulu, aku akan sangat senang menerima mereka. Aku juga takut, ketika aku mulai menerima mereka, mereka malah akan meninggalkanku.
Hey, aku jadi teringat sahabat masa kecilku. Aku sangat menyayanginya, sampai-sampai aku memberikan semua kepercayaanku padanya. Harus kukatakan, ketika pusat kenyamananku hilang, dialah yang bisa menampung keluh-kesahku.
Namun, kurasa, ia juga lelah mendengarkanku. Sama dengan hilangnya kenyamananku, ia juga meninggalkanku dan mementingkan kisah cintanya daripada aku. Aku hampir memaafkannya, aku hampir menerima kesalahannya. Sampai ia akhirnya, mengecewakanku lebih dalam.
Bagaimana perasaanmu kalau sahabat yang sangat kau percaya mengatakan bahwa ia berteman denganmu hanya karena orang tuanya menyuruhnya untuk berteman dengan anak dari seseorang yang berpengaruh?
Jujur saja, aku jadi takut dengan setiap perkenalan. Takut terlalu dekat, terlalu erat. Dan akhirnya, dikecewakan, dilupakan. Aku takut, tapi hampir tidak bisa menghindarinya. Lalu, apa yang aku lakukan dengan hubungan pertemanan yang hanya menakutiku dan mengkhianatiku? Apa pola yang akan muncul dari pengkhianatan?
Balas dendam. Aku tidak ingin berubah menjadi sosok yang melampiaskan kekesalanku kepada orang-orang yang menerimaku sebagai teman mereka. Mata dibayar mata, api dibalas api. Pola pikir semacam itu adalah akar peperangan.
Kalau pada akhirnya, aku diterima sebagai seorang sahabat yang dapat dipercaya lalu keinginan balas dendam malah merasukiku, maka untuk apa aku berteman? Aku benar-benar takut. Aku benar-benar tidak ingin. Tidak ingin menjadi seorang pengkhianat.
Aku menepiskan lamunanku. Kembali hadir di detik ini. Cepat, aku mengalihkan pandanganku ke jalan.
Lampu berubah hijau.
Dari sebelah kanan, sebuah motor menyejajari mobil kami. Motor matic berwarna perak. Pengemudinya adalah seorang bapak awal 50 tahunan yang mengenakan helm butut, tampangnya sederhana, dengan kumis tebal dan sinar mata yang ramah. Ia membonceng seorang wanita bersama anak kecil, yang juga sederhana.
Wanita itu menggenggam tangan si anak kecil. Dan kehangatan wajah mereka bertiga, seperti nyala api di tengah hutan yang dingin. Tenang, walau mereka hanya mengendarai sebuah motor di tengah teriknya matahari sore. Mungkin mereka dalam perjalanan pulang ke rumah. Sama sepertiku. Ah, sama namun kenyataannya tidak serupa.
Aku kembali terusik.
Di sisi lain jalan, ada sepasang kakek dan nenek, tampak sedang mengumpulkan sampah di dekat bangku taman kota. Mereka tidak lagi muda, tapi lihat wajah mereka. Aku tercekat. Mereka tampak bahagia dan betapa kuat rasa percaya yang terpancar di wajah mereka masing-masing.
Dengan wajah-wajah itu, mereka tabah mengumpulkan sampah yang telah mengalahkan keasrian taman, asalkan tetap dibiarkan berdua. Satu pertanyaan membayangiku: Apa Ayah dan Bunda tidak ditakdirkan untuk tetap dibiarkan berdua seperti mereka?
»«
10 Maret 2019, pagi hari
Meja makan ini terasa lengang. Sinar matahari pagi menerobos masuk lewat kerai jendela. Aroma dari sisa embun yang mulai naik memenuhi rongga hidungku. Aku memandangi jendela panjang seruangan yang berjarak kurang lebih tiga meter dari meja makan, masih ada sisa embun disana.
Bagaimana, ya, rasanya menyenderkan kepala di sana? Menempelkan dahiku di bidangnya. Aku ingin meresapi sensasi dinginnya, menikmati keheningan di saat matahari masih malu-malu melepaskan sinarnya.
Aku mengalihkan pandanganku, memerhatikan pantulan ruang makan dari kaca jendela itu. Sangat luas. Di ujung sana, kulihat pantulan Ayah yang menyantap sarapannya sambil terus membaca koran pagi yang tadi dilemparkan petugas ke teras rumah.
Aku menangkap pantulanku. Aku tersenyum miris, apa aku memang terlihat semenyedihkan itu atau hanya perasaanku saja? Namun, tentu saja, perasaanku menyiratkan bahwa aku memang menyedihkan.
Kembali, kuperhatikan pantulan ruang makan itu. Terlihat lengang. Entah karena di rumah besar ini hanya tinggal aku dan Ayah, entah karena memang ada jarak yang terus tercipta. Sama sekali tidak berwarna.
Aku menunduk menghadapi piring, menunggu saat-saat tepat untuk mulai berbicara. Untuk mengingatkan hari apa ini.
“Marista,” panggil Ayah, lagi-lagi tidak menatapku langsung, hanya terpaku pada koran yang dibacanya.
“Ya, Yah?” aku mengikuti Ayah, hanya terpaku pada piring didepanku yang hampir tidak tersentuh.
“Ada masalah yang bisa Ayah bantu?”
Aku menunduk semakin dalam. Ya, Yah. Aku sangat merindukan Bunda. Bisakah kita kembali ke masa lalu dan tidak perlu merana?
“Kalau Ayah ada salah sama kau, bilang saja. Jangan dipendam-pendam.” Ayah membalik korannya, membaca halaman selanjutnya. “Kau kok jadi jarang bicara akhir-akhir ini?”
Akhir-akhir ini? Seberapa lama ‘akhir-akhir ini’ bagi Ayah? 10 tahun? “Tidak ada yang salah, Yah. Aku cuma lagi mikirin tugas-tugasku yang sedang menumpuk,” Ayah memang tidak bersalah. Siapapun tidak bersalah. Walau, aku ingin sekali menghujat keadaan ini. Tapi, harus bagaimana lagi? Tidak ada yang bisa disalahkan. Tidak ada yang bisa kusalahkan atas semua masalah yang hadir.
“Begitu? Cobalah kau cicil tugas-tugasmu yang menumpuk. Jangan dibiarkan terus menumpuk. Hidup kau kan isinya bukan soal tugas sekolah tok, nak,” ayolah, Yah, hidup Ayah juga bukan melulu soal kerja.
“Iya, Yah. Akan aku usahakan,” Apa Ayah tidak pernah menengok kamarku? Lihatlah meja belajarku, tidak ada satu pun tugas yang menumpuk. Apa Ayah tidak bisa mendeteksi alasanku yang terlalu kentara? Terima kasih atas kepeduliannya, Yah. Bahkan, Bunda tidak akan mengatakan itu padaku.
“Teman Ayah kemarin telepon ke kantor. Akan ada seminar mengenai manajemen bisnis di kampus ajarannya minggu depan. Kau ikut, ya? Ajak juga teman-teman dekatmu,”
Refleks, aku melengos. Siratan yang bagaimana lagi yang harus aku tunjukkan pada Ayah bahwa aku tidak memiliki teman dekat? Lebihnya lagi, aku capek membayangkan harus mendengarkan ocehan tentang bisnis yang tidak kumengerti seharian. Bosan menjawab pertanyaan ‘kau anak Pak Arwin, ya?’.
Bosan dengan perlakuan mereka yang berlebihan setelah mengetahui siapa ayahku. Bosan dengan adegan-adegan sama yang berulang-ulang terus setiap aku mengikuti perintah ayah untuk ikut seminar-seminar omong kosong itu. Bosan. Bosan. Bosan.
“Kenapa? Kau ada kerja kelompok?” bagaimana mungkin Ayah melontarkan pertanyaan itu sementara matanya terus terpaku pada koran itu? Apa Ayah bahkan membaca perubahan raut wajahku?
“Nak, seminar seperti itu kan tidak setiap hari ada. Luangkan waktumu,” aku tertawa, hanya dalam hati. Yah, apa yang akan aku katakan ini juga tidak setiap hari terjadi. Apa Ayah mau meluangkan waktu Ayah?
“Yah,” panggilku. Saatnya aku mengingatkan Ayah.
“Hm?” bodohnya aku berpikir Ayah akan melepaskan tatapannya dari halaman koran itu.
“Ayah tau ini hari apa?” selidikku. Ayolah, cobalah mengingatnya, Yah.
“Kamis?” Ayah balik bertanya, sambil membaca halaman berikutnya.
Aku menatap lurus pada Ayah, “Hari ini ulang tahun Bunda.” Waw, sekarang Ayah baru mendongakkan kepalanya. Menatap jauh kedalam mataku. Lihat, perubahan raut wajah Ayah.
“Nak, untuk apa orang yang telah meninggal kau ingatkan hari ulang tahunnya?” Hm, setiap tahun Ayah melemparkan pertanyaan ampuh itu padaku. Aku mampu menghitung detik keampuhannya. Namun, aku tidak tahu berapa banyak luka yang telah ditorehkan oleh kalimat itu.
Ayah terdengar menghela nafas panjang. “Ayah mohon, tumbuhlah dewasa. Kalau kau terus bersikap seperti ini, Ayah takut kau akan depresi,” akhirnya, Ayah tidak terpaku pada koran menjengkelkan itu. Ya, walaupun koran itu tetap dipegangnya erat.
“Aku hanya mengingatkan, Yah. Setidaknya hanya hal kecil ini yang bisa kuingat tentang Bunda,” aku ingat semuanya, tapi apa perlu aku katakan itu sementara Ayah tampak tidak peduli?
“Apa sesulit itu hidup seperti apa adanya, Nak?”
Aku tidak tau, Yah. Jika kukatakan benar—sangat sulit—tapi, aku mampu melewatinya sampai detik ini. Aku bisa melewati masa-masa sulit itu. Memendam rasa sulit itu sendiri. Memikul beban sulit itu di pundakku sendiri.
Jangan suruh aku berbagi kesulitan itu pada Ayah. Karena aku tidak mampu menahan tangisku jika aku menceritakan ini pada Ayah. Biarlah kita tanggung kesulitan masing-masing saja. Terkadang, keegoisan lebih baik daripada tampak saling peduli namun semakin tersakiti.
Well, aku juga tidak akan mengatakan bahwa hidup seperti apa adanya itu mudah. Sama seperti Ayah yang harus membangun semangat lagi, aku juga demikian. Kita sama-sama tau, Yah. Ini tidak mudah. Memperbaiki tembok yang telah hancur sepenuhnya sama saja dengan membangunnya dari awal. Dari titik dimana semuanya nol. Dan sebagai pebisnis, Ayah tau itu dengan pasti.
Baiklah, Ayah mungkin tidak tau perasaanku ketika Ayah mengenalkan aku pada semua wanita yang Ayah sukai. Yang Ayah pikir bisa menggantikan posisi Bunda untukku. Tapi sampai sekarang apa Ayah menemukan sosok seperti Bunda pada semua wanita yang Ayah kenal? Tidak, kan? Lalu, kenapa Ayah harus bertanya dan terus bertanya: apakah sulit hidup seperti apa adanya? Ayolah, Yah, bahkan hidup itu memandang ada apanya untuk terus jalan kedepan.
Berapa kali juga aku harus menyiratkan pada Ayah bahwa bagiku ibuku cuma satu dan itu adalah Bunda?
Meja makan ini seperti masuk pusaran waktu dimana satu detik serasa satu abad. Menggenangi aku dengan perasaan rapuh. Dan membanjiri aku dengan ketabahan. Tidak ada yang muncul ke permukaan. Semuanya hanya berputar pada pusaran itu. Sampai aku pusing sendiri dan terduduk di detik ini ketika kudengar panggilan Ayah.
“Nak?”
“Ya, Yah?”
“Apa agendamu hari ini?”
“Hanya di sekolah, mengerjakan mading,” Ayah harus tahu ini bohong.
“Tidak ada yang lain?” Apa perlu bertanya? Tentu saja ada.
“Tidak, aku tetap di sekolah sampai sore, seperti biasa,” seperti biasa, aku bohong.
“Baiklah,” Ayah melipat korannya. Beranjak dari duduknya, “Sekarang, kita berangkat.” Ayah menenteng tas kerjanya dengan angkuh, mendahuluiku.
Aku mengangguk, ragu. Apa Ayah benar-benar mengenalku? Apa Ayah tidak bisa mendeteksi kebohongan di mataku? Apa aku terlihat begitu tenang dalam menyampaikan kedustaan? Apa Ayah pernah memikirkan perasaanku? Apa Ayah telah lupa bagaimana bahagia kami dulu? Harus berapa banyak pertanyaan yang harus kuteriakkan dalam hati?
Aku termenung. Di dalam rumah sebagus ini, selama sepuluh tahun terakhir, aku tidak pernah benar-benar merasa meninggalinya. Aku ingin mengakhirinya. Aku ingin menyudahinya.
“Aku ingin menemui Bunda,” gumamku lemah. Memandang punggung Ayah yang tampak tidak peduli bahkan kalau aku berteriak sekalipun.
»«
10 Maret 2019, pukul 3 sore
Aku menatap keluar jendela sambil memegang ponselku, gemetaran. Ragu, harus mengirim pesan ini pada Ayah atau tidak. Bagaimana kalau setelah menerima pesan ini, Ayah justru mengirimkan anak buahnya untuk menengok keadaanku ke sekolah? Tunggu, kenapa aku harus berpikir seperti itu? Ayah tidak akan sepeduli itu. Aku tertawa miris. Baiklah, mari kita kirim pesan ini.
Untuk: Ayah 0853 xxxx 7333
Hari ini, aku benar-benar repot mengerjakan mading kelas. Mungkin aku pulang agam malam. Nanti aku pulang bersama teman. Tidak perlu khawatir, Yah. Aku tidak akan pulang lebih dari jam 8 malam.
Kirim!
Aku menghela nafas. Sekarang, apa? Menunggu balasan dari Ayah? Atau aku melanjutkan perjalanan ini saja?
Pada jam segini, tidak banyak kendaraan umum dan mobil pribadi yang berlalu-lalang. Memang seharusnya begitu, ini bukan jam-jam pulang kerja. Malah waktu yang tepat untuk Ayah mengadakan rapat bersama bawahan dan rekan-rekannya. Atau siapa pun itu. Masa bodohlah, mari lanjutkan saja perjalanan ini.
Ting!
Belum sempat aku menaruh kembali ponselku ke saku seragam, sebuah pesan masuk. Dari Ayah! Apa sekarang ia sedang tidak ada rapat seperti beberapa hari belakangan? Cepat sekali membalas pesanku. Aku tersenyum, entah untuk apa.
Dari: Ayah 0853 xxxx 7333
Jaga diri baik-baik. Kalau sudah selesai, langsung pulang. Pak Ben mungkin bisa jemput kalau temanmu tidak bisa mengantarkanmu pulang. Kasih tau Ayah kalau sudah selesai. Sekarang, Ayah sedang ada rapat.
Aku merasakan bagaimana senyumanku mengendur. Ternyata ekspektasiku tentang definisi peduli terlalu tinggi dan aku menyesali perasaan tinggi itu. Mana mungkin aku berpikir kalau Ayah akan menengokku di sekolah? Tunggu, aku juga tidak akan di sekolah ketika hal itu benar-benar terjadi! Apa yang sedang kupikirkan?! Bukannya tadi aku sudah mengatakan masa bodoh?
Untuk: Ayah 0853 xxxx 7333
Aku tau, Yah. Semoga sukses dengan rapatnya.
Ya, semoga sukses dengan rapat omong kosong itu.
Sebentar, kenapa sih supir taksi satu ini dari tadi mencuri-curi pandang lewat spion depan, padaku? Aku jadi heran. Dari perawakannya, tampaknya usianya tidak jauh diatasku. Tunggu, mungkinkah ia sudah lulus SMA? Bagaimana mungkin seorang anak SMA dibiarkan berprofesi menjadi supir taksi?! Tadi, aku buru-buru ingin segera pergi meninggalkan sekolah, jadi tidak peduli dengan si supir. Aku jadi cemas, apa ia sudah punya SIM?! Kumohon, jangan sampai ada razia!
“Kupikir kita satu sekolah? Apa mereka sudah pulang?” tanyanya sambil mengalihkan pandangannya pada jalan.
Apa-apaan pertanyaan itu? Ia tampak tidak canggung melontarkan pertanyaan itu, maksudku pertanyaan itu lebih pantas untuknya. Tidak tahu mau menjawab apa tanpa sakartik, maka aku memilih untuk diam saja.
Ia mencuri pandang lagi, “Kau juga bolos ya? Aku sendiri sedang menggantikan Bapakku.”
Hebat, pertanyaan itu telah dijawab. Aku menganggukkan kepalaku, tentu saja masih memilih untuk menanggapinya dalam diam. Namun, aku masih cemas dengan keberadaan SIM-nya.
“Maaf, sebenarnya kau mau diantar kemana?”
Aku benci menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ditambah suasana hatiku yang sedang tidak baik. Aku menghela nafas, “Kemana saja. Asal bukan di kota ini lagi.”
Ia tampak berpikir sekarang, raut wajahnya menampakkan bahwa ia baru menyadari sesuatu, “Apa kau berniat kabur dari rumah?” Sial, sebaiknya aku diam saja.
Ia memandangku lewat kaca spion depan, kali ini bukan mencuri pandang, tersenyum ramah. “Baiklah, aku tahu kau perlu pergi kemana.” Sinar matanya teduh, sudah lama aku tidak menyelam kedalam tatapan sehangat dan seteduh itu. Astaga, apa yang kupikirkan?!
Demi menyembunyikan rona wajahku, kualihkan wajahku dari tatapannya.
“Ada apa? Kalau kepanasan pindah ke samping sana aja, wajahmu merah begitu,” ujarnya.
Apa?! Bodohnya aku, memalukan. Mau tidak mau, aku bergeser, kini posisi dudukku, berseberangan dengannya. Profil wajahnya dari samping tampak—sial!
Ia melajukan taksi semakin cepat, sudah kubilang ‘kan jalanan cukup lengang tanpa kendaraan umum dan mobil pribadi. Kusenderkan kepalaku, kembalilah kebiasaan itu. Seperti cuplikan yang dipercepat, gedung-gedung tampak seperti mundur menjauh.
Namun, semakin lama, gedung-gedung itu berubah menjadi rumah-rumah rakyat yang khas. Pohon-pohon yang tadinya jarang, sekarang, tampak berlomba menghadirkan diri. Aku rindu suasana ini, sudah lama aku tidak melewati jalanan seperti ini. Kau tahu, ‘kan, kabur dari rutinitas pelajar itu sulit.
Apalagi kalau aku harus mencari alasan yang terlihat tidak terlalu kentara. Ya, walaupun, Ayah tidak tampak peduli dan tidak akan memerhatikan apa alasanku masuk akal atau tidak. Tanpa sadar, senyumku terkembang, senyum miris.
Bugh!
Refleks, aku mengaduh kencang.
Ia tampak melirikku lagi, “Oh, maaf, apa kau baik-baik saja?” suaranya terdengar cemas, sudah lama aku tidak mendengar suara cemas setulus itu.
Tunggu dulu. Bagaimana mungkin ia masih bisa melontarkan pertanyaan sebodoh itu setelah mendengarku mengaduh kencang? Apa yang akan kau rasakan kalau tengkorak kepalamu bertepuk dengan benda sekeras kaca jendela mobil? Tentu saja, aku tidak baik-baik saja!
“Iya, aku baik-baik saja,” jawabku. Tidak ada pilihan lain selain menggunakan kalimat itu. Aku sedang malas meladeni kepedulian seseorang, apalagi dari orang yang baru kukenal beberapa menit ini. Walau dia (mungkin) satu sekolah denganku.
“Untunglah, padahal kedengarannya benturannya cukup keras.” Nah, kau juga berpikir aku pasti tidak akan baik-baik saja, ‘kan?
Taksi itu berhenti.
Aku menyerahkan uang taksi padanya. Ia menyambutnya dengan dua tangan, sopan sekali.
“Terima kasih,” ucapku—oh bukan, aku mengatakannya nyaris seperti bergumam.
Ia memamerkan senyumnya, “Terima kasih kembali,”
Aku membuka pintu taksi, menutupnya kembali setelah aku turun dari kendaraan ini. Aku menoleh, mengapa ia juga turun?
“Aku yang membawamu kemari. Kupikir kau butuh pencerahan.” ujarnya sembari mengayunkan jari ke arah papan nama TPA, ia sudah berdiri tepat disampingku. Sontak aku tersadar akan aroma tidak sedap dalam atmosfer disini. Aku menutup hidungku. Menatapnya sebal.
Ia tersenyum lagi. Kenapa ia masih dengan mudahnya mengembangkan senyum? Begini, disini benar-benar membuatmu tidak bisa bernapas. Coba lihat kondisi sekitar. Kepulan asap dari bukit sampah itu benar-benar menyebalkan. Aku hampir tidak bisa membedakannya dengan awan.
Ia memperhatikan alas kakiku. “Mau coba ke atas?” Aku mengernyit.
Lalu ia memimpin jalan menuju puncak bukit sampah itu. Entah karena pikiranku yang sudah kacau. Aku mau saja diajaknya. Tampaknya sudah ada jalan menuju ke atas sana. Tetap saja sulit bagiku untuk tidak merasa was-was berjalan di tengah sampah ini.
Ia berhenti di tengah jalan. “Lihatlah ke bawah. Kau harus percaya bahwa di dalam rumah-rumah itu masih terdapat kehangatan.” Aku mengikuti arah pandangnya. Di bawah sana, tampak beberapa anak kecil yang masih asik bermain. Walau sebentar lagi akan ada senja yang menjemput kewajibannya.
Ia melanjutkan langkahnya. Hampir sampai di puncak, aku melihat tenda-tenda pengepul sampah. Aku baru saja ingin bertanya ketika ia jongkok di hadapanku. Ia memperhatikan tumbuhan kecil yang bertahan hidup di tengah-tengah tumpukan sampah ini. Aku mengikutinya
“Mungkin ini terlihat aneh. Tapi melihatnya tumbuh disini pasti merupakan tanda adanya harapan. Kau setuju?“ ucapnya. Aku menoleh padanya, mendapati dirinya sudah terpaku pada mataku.
“Aku tidak tahu masalah apa yang sedang kau hadapi. Aku membawamu kesini untuk memperlihatkan padamu. Bahwa penderitaan pasti akan berlalu. Dan setelahnya pasti akan ada kedamaian.”
“Bukankah perkenalan harusnya kita lakukan?” tanyanya,—jangan, jangan tunjukkan senyum itu lagi.
Tunggu. Astaga, pikiranku terlempar ke momen ketika aku membuang-buang makanan. Percakapan bersama Bunda yang telah terkubur dalam perasaan sepiku, mengapa aku pernah melupakan cuplikan berharga ini, Tuhan?
“Kau tau, Sayang, di dunia ini tidak ada yang abadi. Setiap momen yang terjadi, bisa jadi momen terakhir kita. Kau tidak akan pernah mengalami masa itu lagi. Oleh sebab itu, nikmati momenmu untuk menghargai banyak hal. Kelak, Sayang, kau akan menyadari bahwa menikmati hari dengan bahagia akan selalu jadi bukti betapa Tuhan menyayangimu.”
Kurasakan air mataku mulai meleleh. Maafkan aku, Bunda. Kupikir, aku bisa menunda pertemuan kita untuk sementara waktu.
Aku menghapus air mataku. Dengan itu pula, aku menghapus keheningan dalam hatiku. Aku tersenyum padanya. Dia menatapku heran. Namun, inilah saatnya, piano berdenting dan mengalun. Mengiringi langkahku menuju semangat yang benar-benar baru dan penuh sukacita.
“Siapa namamu?” tanyaku, ramah.
Laki-laki ini berubah gugup, mungkin terkejut dengan keramahan suara dan lembut senyumku. Namun, bola matanya bersinar indah. Apa bola mataku juga sama bersinarnya? Aku—tidak ada yang bisa memungkirinya, ternyata disanalah hatiku tertambat. Di sinar mata yang sudah mendobrak kungkunganku, tempatku menikmati keheningan. Sinar mata yang mengingatkanku pada betapa keheningan telah menghanyutkanku dari warnanya kehidupan.
“Namaku Marista Oxavia,” kuulurkan tanganku padanya, dengan gugup ia menyambut tanganku. Kehangatan menjalar keseluruh tubuhku, aku merindukan sensasi ini.
Selama beberapa detik, hanya angin yang mengisi jarak antara kami. Genggaman tangan ini, seakan-akan menghentikan waktu. Dimana aku bagai tenggelam kedalam secercah cahaya dari sinar mata teduhnya. Jangan—aku ingin terus menikmati damai ini.
“Ferre,” ucapnya, ia tersenyum lagi. “Ferre Darius Putra,” tatapan hangat itu benar-benar telah melelehkanku. Untuk pertama kalinya, aku menikmati keheningan ini dengan hati yang terbuka.
Laki-laki ini—Ferre, mengalihkan pandangannya ke genggaman tangan kami. Astaga!
Refleks, aku melepaskan tanganku. Walau sebenarnya aku belum mau melepaskannya.
Ferre menatapku, “Gelap bukan berarti tidak ada cahaya. Gelap berarti butuh cahaya. Dan untuk itu kau perlu membuka penghalangnya,”
Aku tersentak, tanpa sadar, aku tertawa. Apa ini benar suara tawaku? Tidak pernahku mendengar tawa selepas ini!
Bagaimana pun, ia ikut tertawa dengan canggung sambil menggaruk belakang kepalanya. Menurutku, tingkahnya itu sangat menggemaskan!
Aku menghentikan tawaku—tetap tersenyum padanya, untuk pertama kalinya, aku merasa tenang setelah kehilangan Bunda. Aku ingin percaya bahwa Ferre adalah cahaya itu.
“Kalau kau mau aku begitu,” Tunggu—Ferre meraih tanganku kembali, “aku akan menerangimu,” Astaga! Tanpa sadar, aku menyuarakan kalimat itu padanya! Aku tidak percaya ini! Maksudku, kami baru bertemu hari ini! Dan aku dengan bodohnya—tanpa sadar—semacam menyatakan cinta padanya!
Aku mengalihkan pandanganku dari genggaman tangan kami yang kembali bersatu, ke mata teduhnya. Bahkan, dari sinar teduh itu, aku hampir percaya bahwa apa yang ia katakan barusan benar-benar tulus. Aku hampir—ya, aku benar-benar jatuh padanya. Entah percaya atau tidak.
Kupikir pilihan benar untuk naik ke taksinya. Pilihan tepat untuk membiarkannya membawaku ke sini. Sekarang pun aku sudah yakin. Tidak perlu lagi aku diam saat penderitaan melewatiku. Yang harus kulakukan hanyalah berlari melewatinya. (redaksi)


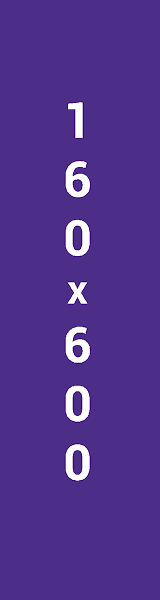




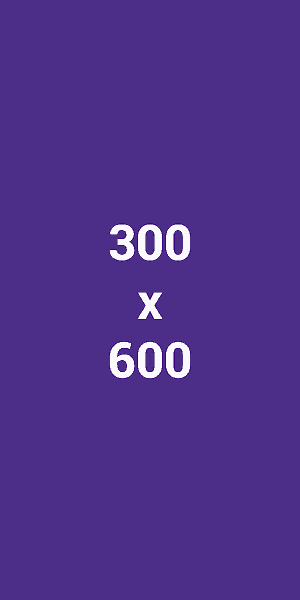



.jpg)

