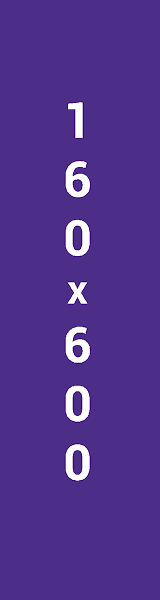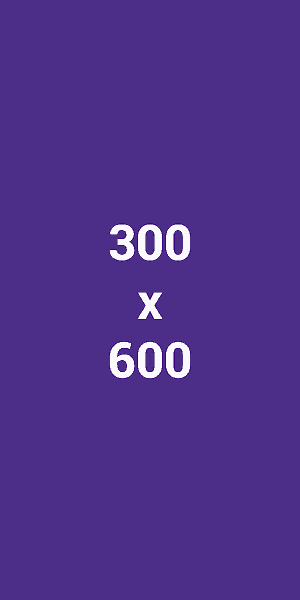Kupikir pilihan benar untuk naik ke taksinya. Pilihan tepat untuk membiarkannya membawaku ke sini. Sekarang pun aku sudah yakin. Tidak perlu lagi aku diam saat penderitaan melewatiku. Yang harus kulakukan hanyalah berlari melewatinya. - Karya Risty Gyro, Sutradara dan Penulis Teater Yupa Unmul -
IDENESIA.CO - 9 Maret 2019, sore hari/
Harus kuakui, ini bukan kali pertama aku merasa benci pada keadaanku. Bukan kali pertama, aku menghabiskan waktuku dengan sia-sia. Kalau aku masih punya tenaga, aku pasti sudah menangis sedari tadi. Namun, emosi yang akan kutumpahkan hanya akan membuatku semakin lelah.
Aku berusaha mengalihkan perasaan kesalku dengan membaca The Adventures of Sherlock Holmes, tapi kemudian yang kudapat hanya pusing di sebelah kanan kepalaku. Mungkin aku bisa menjerit dan memaki—tidak jadilah, nikmati saja keheningan ini. Aku ingin menyalahkan cuaca hari ini.

Aku mengambil ponselku di saku baju yang kukenakan. Menatap miris pada layar ponselku, selama 3 jam 28 menit aku duduk di halte itu. Dibandingkan kemarin, sepertinya hari ini aku menunggu sedikit lebih lama. Seingatku, kemarin, aku menunggu sekitar 3 jam 14 menit.
Baiklah, kusadari semakin hari semakin panjang durasi waktu yang kubutuhkan untuk menunggu. Bisa saja sih, aku menumpang pada teman-teman—ah, aku lupa, mereka terlalu sibuk dengan kegiatan-kegitan personal mereka. Atau bisa saja sih, aku naik angkutan umum—tidak, deh, aku benci suasana pengapnya. Jalan kaki? Jangan paksa aku melakukannya. Aku terlalu lelah, bahkan untuk menggerakkan kakiku.
Ditambah lagi, terjebak di tengah kemacetan kota ini. Bahkan, dibandingkan terjebak seperti ini, aku memilih untuk tersesat di hutan rimba saja. Sore yang seharusnya kunikmati dengan indah, masih kuhabiskan dengan terjebak dalam baju seragamku.
Aku mungkin saja menahan emosiku, tapi tubuhku tidak bisa. Aku yakin sekali, tubuhku ini sudah mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Bahkan, ketiakku sudah menangis duluan. Perutku pun sudah merengek. Kakiku sudah tertidur dan otakku sudah mengantuk.
Kusenderkan kepalaku ke jendela mobil. Merasakan rambatan terik matahari dibidangnya. Mataku menjelajahi setiap jengkal kehidupan di jalan sore itu, kebiasaan yang kulakukan akhir-akhir ini. Membayangkan bagaimana kalau aku berada diluar sana, bukan didalam mobil yang suhunya sengaja diatur sedingin mungkin.
Bagaimana kalau aku yang jadi model di reklame iklan shampo itu? Bagaimana kalau aku hidup di dalam videotron disana itu? Bagaimana kalau aku yang menjajakan makanan kecil di seberang jalan itu? Bagaimana kalau aku yang membersihkan jendela mobil di depan itu? Bagaimana kalau aku yang berada di atas motor bersama seorang ibu muda itu? Bagaimana sih hidup di jalan itu? Apa mereka juga seperti aku?
“Ayah, berapa lama aku harus menunggu lagi, besok?” tanyaku lemah, sebisa mungkin tidak terdengar sarkastik.
Ayahku tertawa. Aku tidak mengerti selera humornya. Sungguh. “Tidak tau, apa kau ada kegiatan sampai sore lagi?”
Masih dengan bersender, membaca plang toko diseberang jalan, aku menggeleng. “Tidak tau, aku belum cek agendaku.” Ya, aku menyusun agendaku sendiri—kalau lagi niat aja sih. Kebetulan sekali, aku banyak waktu luang—sembari menunggu, sesekali aku mencoba menyusun agendaku selama satu bulan kedepan—di halte, tempat biasa aku frustasi sendiri.
Ayah tertawa lagi, “Ayah juga, nak. Kita lihat besok saja.”
Aku tidak menyahut. Tidak juga mengangguk. Hanya diam. Menikmati deru kendaraan yang ingin lekas kembali ke rumah. Bahkan, mobil kami ikut menggeram bersama deruan itu. Lampu merah didepan itu pun, akhirnya, berkedip dan berubah warna menjadi hijau. Tahu maksudku, ‘kan?
Mobil dipacu Ayah membelah jalanan kota dengan pelan. Karena, kalau terlalu cepat, nanti bisa menabrak mobil hitam didepan kami atau mungkin saja menyerempet trotoar dan menyenggol pengamen kecil berbaju hijau muda didepan sana.
Kepalaku terantuk-antuk mengenai kaca jendela mobil, sekali lagi mengamati kendaraan-kendaraan yang berdesakan di jalan kota, sore ini. Membaca hampir semua plat kendaraan yang terlewati. Tidak juga melewatkan tulisan-tulisan aneh atau dekorasi nyentrik yang tertempel di kaca jendela mobil lain. Kebiasaan lain yang mulai muncul.
Sayangnya, kini semua itu tidak lagi bermakna, berbeda dengan mata bocahku dulu. Mata yang sama, manusia yang sama, tapi pandangan yang sama sekali lain. Keluarga yang berbeda.
Seperti siang dan malam, di bumi yang sama tetapi dengan langit yang berbeda. Di rumah yang sama tetapi dengan keluarga yang berbeda. Tidak juga, sih. Bagaimana, ya, pokoknya begitu, deh. Ada saat tatkala kata terasa sia-sia.
Kami berhenti lagi. Aku menghela nafas, tidak tau sudah berapa kali aku melakukannya. Tidak tau sudah berapa lampu lalu lintas yang mencegat jalan mobil kami.
Sekalipun sulit, tapi pikiranku berusaha keras untuk kembali. Kembali mengingat masa bocahku, bermain bebas di halaman belakang yang luas dengan senyum yang terus mengembang. Dulu, aku juga tidak pernah kesepian. Selalu saja ada Bunda yang menemani.
Hidup ternyata lucu, seringku tertawa-tawa karenanya. Bukan maksudku menertawakan takdir dan hal semacamnya. Aku percaya akan takdir yang sudah ditorehkan di atas kertas kekekalan. Tapi kemudian pikiranku mensinyalir sesuatu.
Ada jejak-jejak keresahan yang tidak pernah terungkap. Mengapa aku selalu sedih dan lelah sekali? Mengapa kebahagian pergi dari hidupku? Mengapa aku harus menyembunyikan jati diriku? Mengapa Bunda meninggalkanku? Mengapa harus aku yang mengalaminya? Mengapa harus lembar kekekalanku yang ditulis takdir menyedihkan macam ini?
Takdir menyedihkan mana lagi yang kau dustai, jika aku katakan aku pernah merasa sangat bahagia—merasa hidupku begitu sempurna—tapi, justru, pusat kebahagianku malah mengecewakanku dan meninggalkanku? Bertahun-tahun lewat sudah, dan aku tetap tidak punya jawaban atas itu semua. Dan dari sanalah kebiasaan itu muncul. Membisu di dalam mobil, membaca semua tulisan yang terlewati, memulai percakapan pada diriku sendiri.
Aku sudah kehilangan pusat kenyamananku—tempat kuberbagi cerita kala masih bocah. Lalu, kemana lagi aku harus bercerita selain kepada diriku sendiri. Silahkan, anggap aku abnormal, aku tidak peduli.
“Marista,” panggil Ayah, aku menoleh malas padanya. Jujur saja, aku juga malas untuk menanggapinya.
“Ayah baru ingat,” ucapnya lagi sambil mengetuk-ngetuk kemudi mobil, “Malam ini, ayah harus lembur. Jadi, Ayah hanya akan antarkan kau pulang. Terus, kembali lagi ke kantor,” Ayah bahkan tidak menatapku ketika ia bicara. Apa aku juga harus menjawab pernyataannya itu?
“Aku mengerti, Yah,” akhirnya aku hanya mengatakan itu. Lalu, kembali ke perjalanan menembus imajiku. Kembali kekeheningan.
Semenjak kehilangan pusat kenyamananku, aku senang menyimak keheningan, daripada harus merongrong minta perhatian. Aku bukan gadis belasan tahun yang aktif dan ceria. Aku sudah membuang sifat itu dari tumpukan dokumen usang di laci kepribadianku.
Rasa sukaku pada keheningan, membuatku jarang membuat masalah, membuatku menjadi murid yang baik. Namun, keheningan memolesku menjadi sosok teman yang tidak menyenangkan. Well, daripada menanggapi gosip murahan tentang anak penjaga kantin yang ganteng tapi tidak bersekolah itu, lebih baik kunikmati alunan musik klasik dari ponselku.
Aku tidak suka menimpali hal-hal yang tidak kuketahui kebenarannya. Kalau sesekali aku menanggapi sesuatu, itu artinya aku dalam suasana hati yang sedang bagus. Sayang sekali, suasana hatiku jarang baik. Lebih baik diam, daripada kulontarkan kata-kata yang menyakitkan.
Terkadang, Ayah bertanya tentang teman-temanku. Jujur saja, aku sudah lama tidak menyukai proses pertemanan. Aku tidak suka saat mereka berniat mengunjungi rumahku. Kalau situasinya sama seperti aku bocah dulu, aku akan sangat senang menerima mereka. Aku juga takut, ketika aku mulai menerima mereka, mereka malah akan meninggalkanku.
Hey, aku jadi teringat sahabat masa kecilku. Aku sangat menyayanginya, sampai-sampai aku memberikan semua kepercayaanku padanya. Harus kukatakan, ketika pusat kenyamananku hilang, dialah yang bisa menampung keluh-kesahku.
Namun, kurasa, ia juga lelah mendengarkanku. Sama dengan hilangnya kenyamananku, ia juga meninggalkanku dan mementingkan kisah cintanya daripada aku. Aku hampir memaafkannya, aku hampir menerima kesalahannya. Sampai ia akhirnya, mengecewakanku lebih dalam.
Bagaimana perasaanmu kalau sahabat yang sangat kau percaya mengatakan bahwa ia berteman denganmu hanya karena orang tuanya menyuruhnya untuk berteman dengan anak dari seseorang yang berpengaruh?
Jujur saja, aku jadi takut dengan setiap perkenalan. Takut terlalu dekat, terlalu erat. Dan akhirnya, dikecewakan, dilupakan. Aku takut, tapi hampir tidak bisa menghindarinya. Lalu, apa yang aku lakukan dengan hubungan pertemanan yang hanya menakutiku dan mengkhianatiku? Apa pola yang akan muncul dari pengkhianatan?
Balas dendam. Aku tidak ingin berubah menjadi sosok yang melampiaskan kekesalanku kepada orang-orang yang menerimaku sebagai teman mereka. Mata dibayar mata, api dibalas api. Pola pikir semacam itu adalah akar peperangan.
Kalau pada akhirnya, aku diterima sebagai seorang sahabat yang dapat dipercaya lalu keinginan balas dendam malah merasukiku, maka untuk apa aku berteman? Aku benar-benar takut. Aku benar-benar tidak ingin. Tidak ingin menjadi seorang pengkhianat.
Aku menepiskan lamunanku. Kembali hadir di detik ini. Cepat, aku mengalihkan pandanganku ke jalan.
Lampu berubah hijau.
Dari sebelah kanan, sebuah motor menyejajari mobil kami. Motor matic berwarna perak. Pengemudinya adalah seorang bapak awal 50 tahunan yang mengenakan helm butut, tampangnya sederhana, dengan kumis tebal dan sinar mata yang ramah. Ia membonceng seorang wanita bersama anak kecil, yang juga sederhana.
Wanita itu menggenggam tangan si anak kecil. Dan kehangatan wajah mereka bertiga, seperti nyala api di tengah hutan yang dingin. Tenang, walau mereka hanya mengendarai sebuah motor di tengah teriknya matahari sore. Mungkin mereka dalam perjalanan pulang ke rumah. Sama sepertiku. Ah, sama namun kenyataannya tidak serupa.
Aku kembali terusik.
Di sisi lain jalan, ada sepasang kakek dan nenek, tampak sedang mengumpulkan sampah di dekat bangku taman kota. Mereka tidak lagi muda, tapi lihat wajah mereka. Aku tercekat. Mereka tampak bahagia dan betapa kuat rasa percaya yang terpancar di wajah mereka masing-masing.
Dengan wajah-wajah itu, mereka tabah mengumpulkan sampah yang telah mengalahkan keasrian taman, asalkan tetap dibiarkan berdua. Satu pertanyaan membayangiku: Apa Ayah dan Bunda tidak ditakdirkan untuk tetap dibiarkan berdua seperti mereka?
»«
10 Maret 2019, pagi hari
Meja makan ini terasa lengang. Sinar matahari pagi menerobos masuk lewat kerai jendela. Aroma dari sisa embun yang mulai naik memenuhi rongga hidungku. Aku memandangi jendela panjang seruangan yang berjarak kurang lebih tiga meter dari meja makan, masih ada sisa embun disana.
Bagaimana, ya, rasanya menyenderkan kepala di sana? Menempelkan dahiku di bidangnya. Aku ingin meresapi sensasi dinginnya, menikmati keheningan di saat matahari masih malu-malu melepaskan sinarnya.
Aku mengalihkan pandanganku, memerhatikan pantulan ruang makan dari kaca jendela itu. Sangat luas. Di ujung sana, kulihat pantulan Ayah yang menyantap sarapannya sambil terus membaca koran pagi yang tadi dilemparkan petugas ke teras rumah.
Aku menangkap pantulanku. Aku tersenyum miris, apa aku memang terlihat semenyedihkan itu atau hanya perasaanku saja? Namun, tentu saja, perasaanku menyiratkan bahwa aku memang menyedihkan.
Kembali, kuperhatikan pantulan ruang makan itu. Terlihat lengang. Entah karena di rumah besar ini hanya tinggal aku dan Ayah, entah karena memang ada jarak yang terus tercipta. Sama sekali tidak berwarna.