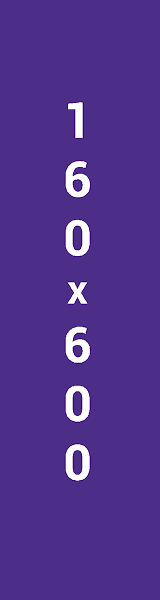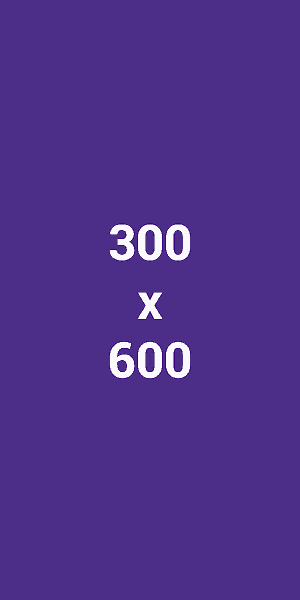Aku menunduk menghadapi piring, menunggu saat-saat tepat untuk mulai berbicara. Untuk mengingatkan hari apa ini.
“Marista,” panggil Ayah, lagi-lagi tidak menatapku langsung, hanya terpaku pada koran yang dibacanya.
“Ya, Yah?” aku mengikuti Ayah, hanya terpaku pada piring didepanku yang hampir tidak tersentuh.
“Ada masalah yang bisa Ayah bantu?”
Aku menunduk semakin dalam. Ya, Yah. Aku sangat merindukan Bunda. Bisakah kita kembali ke masa lalu dan tidak perlu merana?
“Kalau Ayah ada salah sama kau, bilang saja. Jangan dipendam-pendam.” Ayah membalik korannya, membaca halaman selanjutnya. “Kau kok jadi jarang bicara akhir-akhir ini?”
Akhir-akhir ini? Seberapa lama ‘akhir-akhir ini’ bagi Ayah? 10 tahun? “Tidak ada yang salah, Yah. Aku cuma lagi mikirin tugas-tugasku yang sedang menumpuk,” Ayah memang tidak bersalah. Siapapun tidak bersalah. Walau, aku ingin sekali menghujat keadaan ini. Tapi, harus bagaimana lagi? Tidak ada yang bisa disalahkan. Tidak ada yang bisa kusalahkan atas semua masalah yang hadir.
“Begitu? Cobalah kau cicil tugas-tugasmu yang menumpuk. Jangan dibiarkan terus menumpuk. Hidup kau kan isinya bukan soal tugas sekolah tok, nak,” ayolah, Yah, hidup Ayah juga bukan melulu soal kerja.
“Iya, Yah. Akan aku usahakan,” Apa Ayah tidak pernah menengok kamarku? Lihatlah meja belajarku, tidak ada satu pun tugas yang menumpuk. Apa Ayah tidak bisa mendeteksi alasanku yang terlalu kentara? Terima kasih atas kepeduliannya, Yah. Bahkan, Bunda tidak akan mengatakan itu padaku.
“Teman Ayah kemarin telepon ke kantor. Akan ada seminar mengenai manajemen bisnis di kampus ajarannya minggu depan. Kau ikut, ya? Ajak juga teman-teman dekatmu,”
Refleks, aku melengos. Siratan yang bagaimana lagi yang harus aku tunjukkan pada Ayah bahwa aku tidak memiliki teman dekat? Lebihnya lagi, aku capek membayangkan harus mendengarkan ocehan tentang bisnis yang tidak kumengerti seharian. Bosan menjawab pertanyaan ‘kau anak Pak Arwin, ya?’.
Bosan dengan perlakuan mereka yang berlebihan setelah mengetahui siapa ayahku. Bosan dengan adegan-adegan sama yang berulang-ulang terus setiap aku mengikuti perintah ayah untuk ikut seminar-seminar omong kosong itu. Bosan. Bosan. Bosan.
“Kenapa? Kau ada kerja kelompok?” bagaimana mungkin Ayah melontarkan pertanyaan itu sementara matanya terus terpaku pada koran itu? Apa Ayah bahkan membaca perubahan raut wajahku?
“Nak, seminar seperti itu kan tidak setiap hari ada. Luangkan waktumu,” aku tertawa, hanya dalam hati. Yah, apa yang akan aku katakan ini juga tidak setiap hari terjadi. Apa Ayah mau meluangkan waktu Ayah?
“Yah,” panggilku. Saatnya aku mengingatkan Ayah.
“Hm?” bodohnya aku berpikir Ayah akan melepaskan tatapannya dari halaman koran itu.
“Ayah tau ini hari apa?” selidikku. Ayolah, cobalah mengingatnya, Yah.
“Kamis?” Ayah balik bertanya, sambil membaca halaman berikutnya.
Aku menatap lurus pada Ayah, “Hari ini ulang tahun Bunda.” Waw, sekarang Ayah baru mendongakkan kepalanya. Menatap jauh kedalam mataku. Lihat, perubahan raut wajah Ayah.
“Nak, untuk apa orang yang telah meninggal kau ingatkan hari ulang tahunnya?” Hm, setiap tahun Ayah melemparkan pertanyaan ampuh itu padaku. Aku mampu menghitung detik keampuhannya. Namun, aku tidak tahu berapa banyak luka yang telah ditorehkan oleh kalimat itu.
Ayah terdengar menghela nafas panjang. “Ayah mohon, tumbuhlah dewasa. Kalau kau terus bersikap seperti ini, Ayah takut kau akan depresi,” akhirnya, Ayah tidak terpaku pada koran menjengkelkan itu. Ya, walaupun koran itu tetap dipegangnya erat.
“Aku hanya mengingatkan, Yah. Setidaknya hanya hal kecil ini yang bisa kuingat tentang Bunda,” aku ingat semuanya, tapi apa perlu aku katakan itu sementara Ayah tampak tidak peduli?
“Apa sesulit itu hidup seperti apa adanya, Nak?”
Aku tidak tau, Yah. Jika kukatakan benar—sangat sulit—tapi, aku mampu melewatinya sampai detik ini. Aku bisa melewati masa-masa sulit itu. Memendam rasa sulit itu sendiri. Memikul beban sulit itu di pundakku sendiri.
Jangan suruh aku berbagi kesulitan itu pada Ayah. Karena aku tidak mampu menahan tangisku jika aku menceritakan ini pada Ayah. Biarlah kita tanggung kesulitan masing-masing saja. Terkadang, keegoisan lebih baik daripada tampak saling peduli namun semakin tersakiti.
Well, aku juga tidak akan mengatakan bahwa hidup seperti apa adanya itu mudah. Sama seperti Ayah yang harus membangun semangat lagi, aku juga demikian. Kita sama-sama tau, Yah. Ini tidak mudah. Memperbaiki tembok yang telah hancur sepenuhnya sama saja dengan membangunnya dari awal. Dari titik dimana semuanya nol. Dan sebagai pebisnis, Ayah tau itu dengan pasti.
Baiklah, Ayah mungkin tidak tau perasaanku ketika Ayah mengenalkan aku pada semua wanita yang Ayah sukai. Yang Ayah pikir bisa menggantikan posisi Bunda untukku. Tapi sampai sekarang apa Ayah menemukan sosok seperti Bunda pada semua wanita yang Ayah kenal? Tidak, kan? Lalu, kenapa Ayah harus bertanya dan terus bertanya: apakah sulit hidup seperti apa adanya? Ayolah, Yah, bahkan hidup itu memandang ada apanya untuk terus jalan kedepan.
Berapa kali juga aku harus menyiratkan pada Ayah bahwa bagiku ibuku cuma satu dan itu adalah Bunda?
Meja makan ini seperti masuk pusaran waktu dimana satu detik serasa satu abad. Menggenangi aku dengan perasaan rapuh. Dan membanjiri aku dengan ketabahan. Tidak ada yang muncul ke permukaan. Semuanya hanya berputar pada pusaran itu. Sampai aku pusing sendiri dan terduduk di detik ini ketika kudengar panggilan Ayah.
“Nak?”
“Ya, Yah?”
“Apa agendamu hari ini?”
“Hanya di sekolah, mengerjakan mading,” Ayah harus tahu ini bohong.
“Tidak ada yang lain?” Apa perlu bertanya? Tentu saja ada.
“Tidak, aku tetap di sekolah sampai sore, seperti biasa,” seperti biasa, aku bohong.
“Baiklah,” Ayah melipat korannya. Beranjak dari duduknya, “Sekarang, kita berangkat.” Ayah menenteng tas kerjanya dengan angkuh, mendahuluiku.
Aku mengangguk, ragu. Apa Ayah benar-benar mengenalku? Apa Ayah tidak bisa mendeteksi kebohongan di mataku? Apa aku terlihat begitu tenang dalam menyampaikan kedustaan? Apa Ayah pernah memikirkan perasaanku? Apa Ayah telah lupa bagaimana bahagia kami dulu? Harus berapa banyak pertanyaan yang harus kuteriakkan dalam hati?
Aku termenung. Di dalam rumah sebagus ini, selama sepuluh tahun terakhir, aku tidak pernah benar-benar merasa meninggalinya. Aku ingin mengakhirinya. Aku ingin menyudahinya.
“Aku ingin menemui Bunda,” gumamku lemah. Memandang punggung Ayah yang tampak tidak peduli bahkan kalau aku berteriak sekalipun.
»«
10 Maret 2019, pukul 3 sore
Aku menatap keluar jendela sambil memegang ponselku, gemetaran. Ragu, harus mengirim pesan ini pada Ayah atau tidak. Bagaimana kalau setelah menerima pesan ini, Ayah justru mengirimkan anak buahnya untuk menengok keadaanku ke sekolah? Tunggu, kenapa aku harus berpikir seperti itu? Ayah tidak akan sepeduli itu. Aku tertawa miris. Baiklah, mari kita kirim pesan ini.
Untuk: Ayah 0853 xxxx 7333
Hari ini, aku benar-benar repot mengerjakan mading kelas. Mungkin aku pulang agam malam. Nanti aku pulang bersama teman. Tidak perlu khawatir, Yah. Aku tidak akan pulang lebih dari jam 8 malam.
Kirim!
Aku menghela nafas. Sekarang, apa? Menunggu balasan dari Ayah? Atau aku melanjutkan perjalanan ini saja?
Pada jam segini, tidak banyak kendaraan umum dan mobil pribadi yang berlalu-lalang. Memang seharusnya begitu, ini bukan jam-jam pulang kerja. Malah waktu yang tepat untuk Ayah mengadakan rapat bersama bawahan dan rekan-rekannya. Atau siapa pun itu. Masa bodohlah, mari lanjutkan saja perjalanan ini.
Ting!
Belum sempat aku menaruh kembali ponselku ke saku seragam, sebuah pesan masuk. Dari Ayah! Apa sekarang ia sedang tidak ada rapat seperti beberapa hari belakangan? Cepat sekali membalas pesanku. Aku tersenyum, entah untuk apa.
Dari: Ayah 0853 xxxx 7333
Jaga diri baik-baik. Kalau sudah selesai, langsung pulang. Pak Ben mungkin bisa jemput kalau temanmu tidak bisa mengantarkanmu pulang. Kasih tau Ayah kalau sudah selesai. Sekarang, Ayah sedang ada rapat.
Aku merasakan bagaimana senyumanku mengendur. Ternyata ekspektasiku tentang definisi peduli terlalu tinggi dan aku menyesali perasaan tinggi itu. Mana mungkin aku berpikir kalau Ayah akan menengokku di sekolah? Tunggu, aku juga tidak akan di sekolah ketika hal itu benar-benar terjadi! Apa yang sedang kupikirkan?! Bukannya tadi aku sudah mengatakan masa bodoh?
Untuk: Ayah 0853 xxxx 7333
Aku tau, Yah. Semoga sukses dengan rapatnya.
Ya, semoga sukses dengan rapat omong kosong itu.