Sebentar, kenapa sih supir taksi satu ini dari tadi mencuri-curi pandang lewat spion depan, padaku? Aku jadi heran. Dari perawakannya, tampaknya usianya tidak jauh diatasku. Tunggu, mungkinkah ia sudah lulus SMA? Bagaimana mungkin seorang anak SMA dibiarkan berprofesi menjadi supir taksi?! Tadi, aku buru-buru ingin segera pergi meninggalkan sekolah, jadi tidak peduli dengan si supir. Aku jadi cemas, apa ia sudah punya SIM?! Kumohon, jangan sampai ada razia!
“Kupikir kita satu sekolah? Apa mereka sudah pulang?” tanyanya sambil mengalihkan pandangannya pada jalan.
Apa-apaan pertanyaan itu? Ia tampak tidak canggung melontarkan pertanyaan itu, maksudku pertanyaan itu lebih pantas untuknya. Tidak tahu mau menjawab apa tanpa sakartik, maka aku memilih untuk diam saja.
Ia mencuri pandang lagi, “Kau juga bolos ya? Aku sendiri sedang menggantikan Bapakku.”
Hebat, pertanyaan itu telah dijawab. Aku menganggukkan kepalaku, tentu saja masih memilih untuk menanggapinya dalam diam. Namun, aku masih cemas dengan keberadaan SIM-nya.
“Maaf, sebenarnya kau mau diantar kemana?”
Aku benci menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ditambah suasana hatiku yang sedang tidak baik. Aku menghela nafas, “Kemana saja. Asal bukan di kota ini lagi.”
Ia tampak berpikir sekarang, raut wajahnya menampakkan bahwa ia baru menyadari sesuatu, “Apa kau berniat kabur dari rumah?” Sial, sebaiknya aku diam saja.
Ia memandangku lewat kaca spion depan, kali ini bukan mencuri pandang, tersenyum ramah. “Baiklah, aku tahu kau perlu pergi kemana.” Sinar matanya teduh, sudah lama aku tidak menyelam kedalam tatapan sehangat dan seteduh itu. Astaga, apa yang kupikirkan?!
Demi menyembunyikan rona wajahku, kualihkan wajahku dari tatapannya.
“Ada apa? Kalau kepanasan pindah ke samping sana aja, wajahmu merah begitu,” ujarnya.
Apa?! Bodohnya aku, memalukan. Mau tidak mau, aku bergeser, kini posisi dudukku, berseberangan dengannya. Profil wajahnya dari samping tampak—sial!
Ia melajukan taksi semakin cepat, sudah kubilang ‘kan jalanan cukup lengang tanpa kendaraan umum dan mobil pribadi. Kusenderkan kepalaku, kembalilah kebiasaan itu. Seperti cuplikan yang dipercepat, gedung-gedung tampak seperti mundur menjauh.
Namun, semakin lama, gedung-gedung itu berubah menjadi rumah-rumah rakyat yang khas. Pohon-pohon yang tadinya jarang, sekarang, tampak berlomba menghadirkan diri. Aku rindu suasana ini, sudah lama aku tidak melewati jalanan seperti ini. Kau tahu, ‘kan, kabur dari rutinitas pelajar itu sulit.
Apalagi kalau aku harus mencari alasan yang terlihat tidak terlalu kentara. Ya, walaupun, Ayah tidak tampak peduli dan tidak akan memerhatikan apa alasanku masuk akal atau tidak. Tanpa sadar, senyumku terkembang, senyum miris.
Bugh!
Refleks, aku mengaduh kencang.
Ia tampak melirikku lagi, “Oh, maaf, apa kau baik-baik saja?” suaranya terdengar cemas, sudah lama aku tidak mendengar suara cemas setulus itu.
Tunggu dulu. Bagaimana mungkin ia masih bisa melontarkan pertanyaan sebodoh itu setelah mendengarku mengaduh kencang? Apa yang akan kau rasakan kalau tengkorak kepalamu bertepuk dengan benda sekeras kaca jendela mobil? Tentu saja, aku tidak baik-baik saja!
“Iya, aku baik-baik saja,” jawabku. Tidak ada pilihan lain selain menggunakan kalimat itu. Aku sedang malas meladeni kepedulian seseorang, apalagi dari orang yang baru kukenal beberapa menit ini. Walau dia (mungkin) satu sekolah denganku.
“Untunglah, padahal kedengarannya benturannya cukup keras.” Nah, kau juga berpikir aku pasti tidak akan baik-baik saja, ‘kan?
Taksi itu berhenti.
Aku menyerahkan uang taksi padanya. Ia menyambutnya dengan dua tangan, sopan sekali.
“Terima kasih,” ucapku—oh bukan, aku mengatakannya nyaris seperti bergumam.
Ia memamerkan senyumnya, “Terima kasih kembali,”
Aku membuka pintu taksi, menutupnya kembali setelah aku turun dari kendaraan ini. Aku menoleh, mengapa ia juga turun?
“Aku yang membawamu kemari. Kupikir kau butuh pencerahan.” ujarnya sembari mengayunkan jari ke arah papan nama TPA, ia sudah berdiri tepat disampingku. Sontak aku tersadar akan aroma tidak sedap dalam atmosfer disini. Aku menutup hidungku. Menatapnya sebal.
Ia tersenyum lagi. Kenapa ia masih dengan mudahnya mengembangkan senyum? Begini, disini benar-benar membuatmu tidak bisa bernapas. Coba lihat kondisi sekitar. Kepulan asap dari bukit sampah itu benar-benar menyebalkan. Aku hampir tidak bisa membedakannya dengan awan.
Ia memperhatikan alas kakiku. “Mau coba ke atas?” Aku mengernyit.
Lalu ia memimpin jalan menuju puncak bukit sampah itu. Entah karena pikiranku yang sudah kacau. Aku mau saja diajaknya. Tampaknya sudah ada jalan menuju ke atas sana. Tetap saja sulit bagiku untuk tidak merasa was-was berjalan di tengah sampah ini.
Ia berhenti di tengah jalan. “Lihatlah ke bawah. Kau harus percaya bahwa di dalam rumah-rumah itu masih terdapat kehangatan.” Aku mengikuti arah pandangnya. Di bawah sana, tampak beberapa anak kecil yang masih asik bermain. Walau sebentar lagi akan ada senja yang menjemput kewajibannya.
Ia melanjutkan langkahnya. Hampir sampai di puncak, aku melihat tenda-tenda pengepul sampah. Aku baru saja ingin bertanya ketika ia jongkok di hadapanku. Ia memperhatikan tumbuhan kecil yang bertahan hidup di tengah-tengah tumpukan sampah ini. Aku mengikutinya
“Mungkin ini terlihat aneh. Tapi melihatnya tumbuh disini pasti merupakan tanda adanya harapan. Kau setuju?“ ucapnya. Aku menoleh padanya, mendapati dirinya sudah terpaku pada mataku.
“Aku tidak tahu masalah apa yang sedang kau hadapi. Aku membawamu kesini untuk memperlihatkan padamu. Bahwa penderitaan pasti akan berlalu. Dan setelahnya pasti akan ada kedamaian.”
“Bukankah perkenalan harusnya kita lakukan?” tanyanya,—jangan, jangan tunjukkan senyum itu lagi.
Tunggu. Astaga, pikiranku terlempar ke momen ketika aku membuang-buang makanan. Percakapan bersama Bunda yang telah terkubur dalam perasaan sepiku, mengapa aku pernah melupakan cuplikan berharga ini, Tuhan?
“Kau tau, Sayang, di dunia ini tidak ada yang abadi. Setiap momen yang terjadi, bisa jadi momen terakhir kita. Kau tidak akan pernah mengalami masa itu lagi. Oleh sebab itu, nikmati momenmu untuk menghargai banyak hal. Kelak, Sayang, kau akan menyadari bahwa menikmati hari dengan bahagia akan selalu jadi bukti betapa Tuhan menyayangimu.”
Kurasakan air mataku mulai meleleh. Maafkan aku, Bunda. Kupikir, aku bisa menunda pertemuan kita untuk sementara waktu.
Aku menghapus air mataku. Dengan itu pula, aku menghapus keheningan dalam hatiku. Aku tersenyum padanya. Dia menatapku heran. Namun, inilah saatnya, piano berdenting dan mengalun. Mengiringi langkahku menuju semangat yang benar-benar baru dan penuh sukacita.
“Siapa namamu?” tanyaku, ramah.
Laki-laki ini berubah gugup, mungkin terkejut dengan keramahan suara dan lembut senyumku. Namun, bola matanya bersinar indah. Apa bola mataku juga sama bersinarnya? Aku—tidak ada yang bisa memungkirinya, ternyata disanalah hatiku tertambat. Di sinar mata yang sudah mendobrak kungkunganku, tempatku menikmati keheningan. Sinar mata yang mengingatkanku pada betapa keheningan telah menghanyutkanku dari warnanya kehidupan.
“Namaku Marista Oxavia,” kuulurkan tanganku padanya, dengan gugup ia menyambut tanganku. Kehangatan menjalar keseluruh tubuhku, aku merindukan sensasi ini.
Selama beberapa detik, hanya angin yang mengisi jarak antara kami. Genggaman tangan ini, seakan-akan menghentikan waktu. Dimana aku bagai tenggelam kedalam secercah cahaya dari sinar mata teduhnya. Jangan—aku ingin terus menikmati damai ini.
“Ferre,” ucapnya, ia tersenyum lagi. “Ferre Darius Putra,” tatapan hangat itu benar-benar telah melelehkanku. Untuk pertama kalinya, aku menikmati keheningan ini dengan hati yang terbuka.
Laki-laki ini—Ferre, mengalihkan pandangannya ke genggaman tangan kami. Astaga!
Refleks, aku melepaskan tanganku. Walau sebenarnya aku belum mau melepaskannya.
Ferre menatapku, “Gelap bukan berarti tidak ada cahaya. Gelap berarti butuh cahaya. Dan untuk itu kau perlu membuka penghalangnya,”
Aku tersentak, tanpa sadar, aku tertawa. Apa ini benar suara tawaku? Tidak pernahku mendengar tawa selepas ini!
Bagaimana pun, ia ikut tertawa dengan canggung sambil menggaruk belakang kepalanya. Menurutku, tingkahnya itu sangat menggemaskan!
Aku menghentikan tawaku—tetap tersenyum padanya, untuk pertama kalinya, aku merasa tenang setelah kehilangan Bunda. Aku ingin percaya bahwa Ferre adalah cahaya itu.
“Kalau kau mau aku begitu,” Tunggu—Ferre meraih tanganku kembali, “aku akan menerangimu,” Astaga! Tanpa sadar, aku menyuarakan kalimat itu padanya! Aku tidak percaya ini! Maksudku, kami baru bertemu hari ini! Dan aku dengan bodohnya—tanpa sadar—semacam menyatakan cinta padanya!
Aku mengalihkan pandanganku dari genggaman tangan kami yang kembali bersatu, ke mata teduhnya. Bahkan, dari sinar teduh itu, aku hampir percaya bahwa apa yang ia katakan barusan benar-benar tulus. Aku hampir—ya, aku benar-benar jatuh padanya. Entah percaya atau tidak.
Kupikir pilihan benar untuk naik ke taksinya. Pilihan tepat untuk membiarkannya membawaku ke sini. Sekarang pun aku sudah yakin. Tidak perlu lagi aku diam saat penderitaan melewatiku. Yang harus kulakukan hanyalah berlari melewatinya. (redaksi)


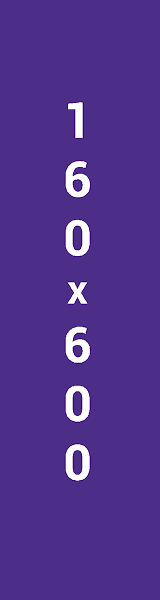




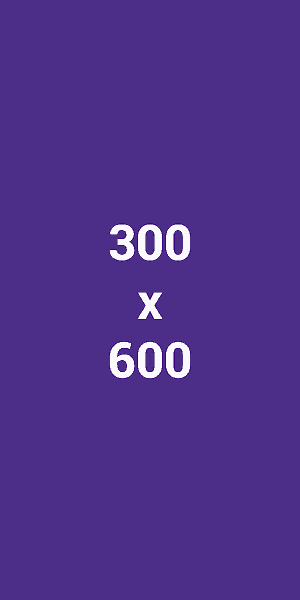



.jpg)

