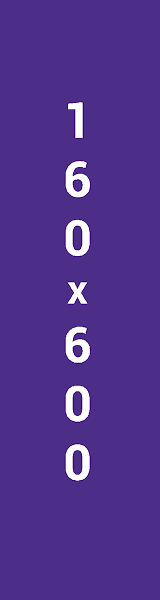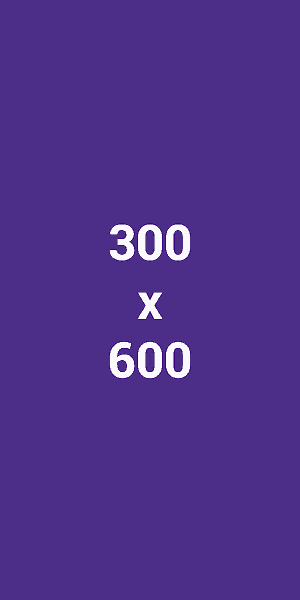Ia begitu tahu cara menyenangkan lelaki yang sangat ia cintai.
Perlahan jemarinya yang halus itu melipir di pundak hingga ke lenganku.
Ibu jarinya menekan kulitku yang tipis, sementara jari lainnya lembut mengusap kulit yang berwarna putih kecoklatan kebanggaanku.
Namun, “Perasaan apa ini?,” seruku dalam hati.
Ada sesuatu yang ganjil, yang masih coba kutebak gerangannya.
Aku masih bertanya kenapa sedari tadi aku tak mampu mengucapkan satu kata pun.
Mengapa kurasakan getaran yang lain, saat dia menyentuh tubuhku, tak seperti biasanya.
Kenapa dia mengalungkan kedua tangannya di leherku, padahal biasanya ia selalu merangkul hanya dengan satu tangan.
Mengapa ia bertanya rindu? Dan menawarkan memijitku, padahal biasanya dia selalu bertanya terlebih dahulu apakah aku sudah makan atau belum.
Pun dengan ciuman pertama yang mendarat tidak di bibirku, mestinya ia menggelitik ketiakku bukan perutku, karena bagian itulah bagian favorit yang selalu dia elukan.
“Kurang ajar, ini lain kursi kesukaanku. Ini miliknya!,” teriak ku lantang namun lagi-lagi masih dalam hati.
Pertanyaan-pertanyaan itu kemudian berkecamuk hebat, seperti hujan lebat yang ditemani guntur dan kilat yang dashyat.
Kemudian tanpa kusadari lagi ia telah duduk di sampingku, tepat di kursi kayu kesukaanku.
Matanya menatap kedepan tajam dan dalam, kemudian menoleh perlahan kearahku sambil merekahkan senyumnya.
Kutatap senyumnya, kemudian aku baru dapat menyimpulkan dan menjawab seluruh pertanyaan yang sedari tadi rusuh di kepalaku.
Aku tarik nafas dalam-dalam untuk mempersiapkan kata sambutanku yang pertama saat kutemui dirinya hari ini.
“Ada apa? Aku siap menerimanya,” kataku.
“kamu kenapa? Sakit ya? Kok serius sekali. Malam ini aku akan masak ikan asin dan sambal goreng kesukaanmu. Sudah lama kita tidak memakannya. Tadi pagi aku juga sempat ke pasar beli bayam dan santan kelapa, aku akan buat sayur santan. Malam ini kita akan makan enak,” balasnya cepat sambil tertawa gelak.
Saat itu aku hanya bisa meneguk air ludah kembali ke dalam, sambil menundukan kepala, air mataku rembes kecil.
Wahai wanita yang amat kucintai, jangan lagi kau sembunyikan.
Aku sudah cukup siap untuk mendengarnya, walaupun jauh sebelum kau utarakan aku telah mengetahuinya.
Aku tahu karena telah ribuan kali wajahmu kusentuh, ribuan kali bibirmu kukecup, tak bisa terhitung sudah berapa kali kupeluk tubuhmu yang mungil kupeluk.
Jangan remehkan laki-laki yang telah mengikrarkan kesetian dan keyakinannya dengan sungguh.
Percayalah kesetian yang telah dipatrikan merupakan wujud dari sebuah konstruksi kebahagian dan masa depan yang sama-sama kita impikan.
“Mau berapa lama lagi kau simpan! Mau sampai kapan kau sembunyikan! Sampaikanlah,” teriakku kali ini tidak dalam hati sambil menggebrak meja kecil di sebelah kananku.
Disaat itulah yang aku yakini tanpa aku harus bertanya atau beretorika panjang lebar, ia memahami apa yang aku maksud.
Percaya atau tidak seketika langit menjadi buram, gemuruh yang dari tadi di kepalaku kini nyata menemaniku saat itu.
Persis seperti di film atau pertunjukan drama teater ketika dua pasang tokohnya telah memasuki tangga konfliknya.
Langit kemudian buram menghitam bukan karena sekedar hujan, namun waktu memang telah senja.
Lantunan adzan maghrib berkumandang ditengah riuh alam bernyanyi sumbang.
Kami masih terdiam mematung, namun aku tahu hati kami berdua sedang bergejolak.
Dan aku tahu wanita yang sedang duduk di sampingku itu tengah menangis, meskipun tak setitik air mata pun keluar dari matanya.