"..Karena aku masih jadi sutradaramu, pertunjukan ini masih belum selesai, mari kita lanjutkan. Seberapa cepat atau seberapa jauh lagi lakon kita berdua, kali ini tidak menjadi penting. Cukup aku tahu, kamu dan aku bermain dengan perasaan yang bahagia..." - Fachri Mahayupa, Sutradara, aktor dan penulis naskah Kalimantan Timur -
IDENESIA.CO - Ada yang lain di senyummu hari ini sayang, kau mungkin bisa berbohong kepada orang lain tapi yakinlah kau tak pandai membohongi mata yang setia melihatmu setiap hari.
Memang benar bibirmu hari ini terlihat begitu merah merona, warnamu pipimu seperti apel malang yang ranum, matamu putih seperti awan sehabis hujan mengguyur bumi --- bersih.
Ya, kau sangat lihai membalut tubuhmu yang lemah itu dengan baja kualitas nomor wahid.
Tapi maaf yang kulihat hanyalah sebuah buaian imaji atas dasar kebohongan yang begitu pahit, ketir dan sadis.

Pun alas kaki yang senada dengan apa yang dikenakannya menambah surga yang sebenarnya telah tertanam di dalam tubuhnya.
Apalagi hari itu ia menggunakan high heels, sempurnalah sudah sesosok bidadari yang kulihat dari kejauhan.
Kadang ingin rasanya aku menemui seseorang yang telah menciptakan benda berukuran tak lebih dari 10 cm di bawah alas kaki bagian belakang itu, aku hanya ingin bilang “Terimakasih bro, karyamu mantap,” bisikku dalam hati.
Entah mengapa angin turut bersahabat ketika aku menikmati momen tersebut. Hembusannya menambah nilai artistik untuk perangai seorang perempuan yang sedang berjalan.
Pada saat itu ia belum melihatku, ia masih asik bercengkrama dengan anak-anak yang melingkari tubuhnya.
Coba bayangkan perempuan yang tidak terlalu gemuk dan kurus berambut hitam dan panjang, kemudian ditemani angin yang bersahabat sehingga setiap helai rambutnya berterbangan hilir-mudik halus, belum lagi dikelilingi anak-anak dengan bola mata yang belum mengenal dosa.
Ia asik berecengkrama mesra, tak ragu bergelak tawa, tangannya ringan mengacak-acak rambut anak-anak itu yang semakin kegirangan terbuai oleh keanggunannya.
Apakah itu bukan surga? Itulah surga.
Aku adalah lelaki yang beruntung yang dapat melihat surga setiap mula dan akhir hari. Kupikir tepat, aku tak memilih neraka dalam tujuan hidupku kelak karena aku ingin menikmati surga yang lebih lagi di kehidupan yang kekal nanti.
“Tuhan, kau memang maha keren,” simpanku nakal.
Aku terpaku seketika itu bukan karena membeku, tapi lumer seperti es batu yang terkena sinar matahari, meleleh.
Ajaib bukan? Namun belum sempat kukedipkan mata, tiba-tiba wajahnya yang manja kini telah berada di hadapanku.
Aku tidak tahu dia menggunakan ilmu apa sehingga dengan cepat dan seketika wajahnya mendarat tepat di depan wajahku.
Astaga, percaya atau tidak mukaku langsung memerah, kepalaku mungkin saja berasap.
Kemudian ia beraksi dengan syahdu dengan menempelkan hidungnya yang tidak terlalu mancung ke hidungku, lalu ia cumbu mesra setiap sisi wajahku tanpa ampun.
Saat itu dia berhasil masuk di timing dan posisi yang tepat, ia berada diatas kedua pahaku yang sedari tadi tengah duduk di atas kursi tua kesukaanku di depan rumah, sembari mengalungkan kedua lengannya yang indah ke leherku penuh.
“Jagoanku sayang apa kabarmu hari ini, do you miss me? pasti lelah sekali hari ini, biar aku pijitin yah,” ucapnya lirih di daun telingaku.
Aku ingin menjawab, tapi belum sempat menjawab ia langsung melancarkan aksi kesukaannya dengan menggelitik beberapa bagian tubuhku.
Tubuhku menggelinjang tak karuan, kemudian kami sama-sama kehabisan nafas.
Tubuhnya yang lemas itu jatuh bersandar persis ditubuhku.
Berat badannya kini bertumpuan dengan dadaku, namun lengannya masih kuat mencengkram batang leherku.
Tak lama berselang perlahan ia mulai melepas cengkramannya, ia angkat tubuhnya dari pahaku.
Bergeser ia ke posisi yang lebih tinggi, tepat dibelakang punggungku.
Ia begitu tahu cara menyenangkan lelaki yang sangat ia cintai.
Perlahan jemarinya yang halus itu melipir di pundak hingga ke lenganku.
Ibu jarinya menekan kulitku yang tipis, sementara jari lainnya lembut mengusap kulit yang berwarna putih kecoklatan kebanggaanku.
Namun, “Perasaan apa ini?,” seruku dalam hati.
Ada sesuatu yang ganjil, yang masih coba kutebak gerangannya.
Aku masih bertanya kenapa sedari tadi aku tak mampu mengucapkan satu kata pun.
Mengapa kurasakan getaran yang lain, saat dia menyentuh tubuhku, tak seperti biasanya.
Kenapa dia mengalungkan kedua tangannya di leherku, padahal biasanya ia selalu merangkul hanya dengan satu tangan.
Mengapa ia bertanya rindu? Dan menawarkan memijitku, padahal biasanya dia selalu bertanya terlebih dahulu apakah aku sudah makan atau belum.
Pun dengan ciuman pertama yang mendarat tidak di bibirku, mestinya ia menggelitik ketiakku bukan perutku, karena bagian itulah bagian favorit yang selalu dia elukan.
“Kurang ajar, ini lain kursi kesukaanku. Ini miliknya!,” teriak ku lantang namun lagi-lagi masih dalam hati.
Pertanyaan-pertanyaan itu kemudian berkecamuk hebat, seperti hujan lebat yang ditemani guntur dan kilat yang dashyat.
Kemudian tanpa kusadari lagi ia telah duduk di sampingku, tepat di kursi kayu kesukaanku.
Matanya menatap kedepan tajam dan dalam, kemudian menoleh perlahan kearahku sambil merekahkan senyumnya.
Kutatap senyumnya, kemudian aku baru dapat menyimpulkan dan menjawab seluruh pertanyaan yang sedari tadi rusuh di kepalaku.
Aku tarik nafas dalam-dalam untuk mempersiapkan kata sambutanku yang pertama saat kutemui dirinya hari ini.
“Ada apa? Aku siap menerimanya,” kataku.
“kamu kenapa? Sakit ya? Kok serius sekali. Malam ini aku akan masak ikan asin dan sambal goreng kesukaanmu. Sudah lama kita tidak memakannya. Tadi pagi aku juga sempat ke pasar beli bayam dan santan kelapa, aku akan buat sayur santan. Malam ini kita akan makan enak,” balasnya cepat sambil tertawa gelak.
Saat itu aku hanya bisa meneguk air ludah kembali ke dalam, sambil menundukan kepala, air mataku rembes kecil.
Wahai wanita yang amat kucintai, jangan lagi kau sembunyikan.
Aku sudah cukup siap untuk mendengarnya, walaupun jauh sebelum kau utarakan aku telah mengetahuinya.
Aku tahu karena telah ribuan kali wajahmu kusentuh, ribuan kali bibirmu kukecup, tak bisa terhitung sudah berapa kali kupeluk tubuhmu yang mungil kupeluk.
Jangan remehkan laki-laki yang telah mengikrarkan kesetian dan keyakinannya dengan sungguh.
Percayalah kesetian yang telah dipatrikan merupakan wujud dari sebuah konstruksi kebahagian dan masa depan yang sama-sama kita impikan.
“Mau berapa lama lagi kau simpan! Mau sampai kapan kau sembunyikan! Sampaikanlah,” teriakku kali ini tidak dalam hati sambil menggebrak meja kecil di sebelah kananku.
Disaat itulah yang aku yakini tanpa aku harus bertanya atau beretorika panjang lebar, ia memahami apa yang aku maksud.
Percaya atau tidak seketika langit menjadi buram, gemuruh yang dari tadi di kepalaku kini nyata menemaniku saat itu.
Persis seperti di film atau pertunjukan drama teater ketika dua pasang tokohnya telah memasuki tangga konfliknya.
Langit kemudian buram menghitam bukan karena sekedar hujan, namun waktu memang telah senja.
Lantunan adzan maghrib berkumandang ditengah riuh alam bernyanyi sumbang.
Kami masih terdiam mematung, namun aku tahu hati kami berdua sedang bergejolak.
Dan aku tahu wanita yang sedang duduk di sampingku itu tengah menangis, meskipun tak setitik air mata pun keluar dari matanya.
Tapi yang kuyakini, tangisan pedih itu bukan di ukur dari seberapa kencangnya teriakan, seberapa derasnya air mata yang mengucur, seberapa hebatnya kita terisak.
Diam, mencoba untuk tetap menegakan kepalanya lurus ke depan.
Itulah cara menangis yang paling mengerikan, dan wanita yang kucintai itu tengah melakukan hal itu.
Aku tahu bagaimana tangis kesakitan yang membanjiri hatinya, kepedihan bak badai yang menghancurkan setiap relung batang tubuhnya, ketakutan yang menyelimuti tubuh mungilnya.
Aku tahu karena aku miliknya, dan ia dalah milikku.
“Mau berapa lama lagi kau simpan! Mau sampai kapan kau sembunyikan! Sampaikanlah,” ucapku sama namun berbeda, lemah dan lirih.
“Aku baru saja dari dokter Irfan, teman lamaku. Maaf, ternyata aku begitu lemah, sayang. Aku belum cukup menjadi wanita tangguh dan terkuatmu,” balasnya lirih.
Sontak, tubuhku bergetar bibirku pucat, dunia seperti berputar cepat memori masa lalu kembali terngiang tentang konsep hidup, konsep kebahagian, prinsip hidup yang kuagungkan.
Kuselami betapa bodohnya aku sebagai lelaki.
Ia bangkit dari kursinya, mengambil sepenggal tanganku.
Kemudian menggelosor di lantai lalu menaruh kepalanya diatas kaki kananku. Kemudian ia berbicara tanpa menatapku.
“Aku hanya tidak ingin kau khawatir, bahkan aku juga tidak ingin kau sampai mengetahuinya.
Agar kau bisa bekerja dengan baik dan fokus, membangun istana kayu yang kita impikan ini.
Kau adalah kebanggaanku, melihatmu membangun istana ini dengan giat merupakan satu-satunya kebahagian terpenting dalam hidupku, aku tidak ingin merusaknya, aku tidak ingin menghancurkannya.
Biarkanlah di sisa hidupku, aku hanya ingin melihat kebahagian yang kita impikan berdua.
Tapi hari ini aku kalah, sayang. Seberapa hebat aku menyembunyikannya, aku yakin kau pasti mengetahuinya sudah.
Aku tahu, karena aku milikmu. Kau memang sutradara terhebatku, tapi kali ini saja aku mohon sebagai aktormu yang nakal.
Jangan meledak lagi, biarkan aku menikmati panggung ini dengan khidmat.
Karena kau sudah menatanya dengan amat baik dan sempurna untuk kita.
Ini sudah lebih dari cukup, tidak akan ada penyesalan barang sedikit di hatiku hidup bersamamu.
Yang perlu kau tahu, kamu adalah satu-satunya lelaki telah membuat aku tahu arti dari sebuah kebahagiaan.
Tidak apa menangislah, sayang. Aku juga rindu air matamu, sudah lama tak kulihat,” tutupnya sambil sedari tadi mengelus dengkulku dengan jari telunjuknya yang halus.
Sungguh, aku ingin teriak sekencangnya, menangis sekerasnya, mengeluarkan kepedihan dan kekalahanku sebagai lelaki yang tak berdaya.
Namun tak bisa. Kelembutan hatinya, mendamaikan segalanya.
Semakin aku paksa untuk menumpahkannya, agar ia tahu betapa aku menyadari kekalahanku, semakin hal tersebut urung tersampaikan.
Tenang aku singkap rambut dan kepalanya, kutuntun tubuhnya berdiri perlahan.
Kurapikan rambutnya yang sedikit berantakan. Lalu kugenggam tangannya damai.
“Karena aku masih jadi sutradaramu, pertunjukan ini masih belum selesai, mari kita lanjutkan. Seberapa cepat atau seberapa jauh lagi lakon kita berdua, kali ini tidak menjadi penting. Cukup aku tahu, kamu dan aku bermain dengan bahagia,” uraiku sembari mencium keningnya.
Namun, seketika pintu istana kami terbuka perlahan.
“Mah, ayo makan malam. Putra lapar nih,” tutur seorang anak gagah memecahkan romantisme saat itu.
Kami ; Gonzalo Fernandez dan Siti Bilqis Aisyah tersentak kaget kemudian saling berpelukan erat.
Kami tidak bisa berdusta, air mata kami tidak berhenti mengalir, deras mengucur, terus membasahi tubuh dan jatuh ke bumi tiada henti. (redaksi)


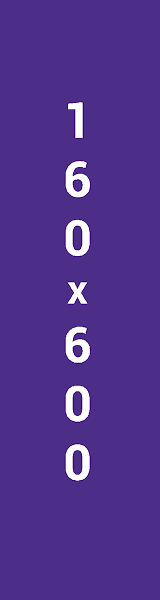



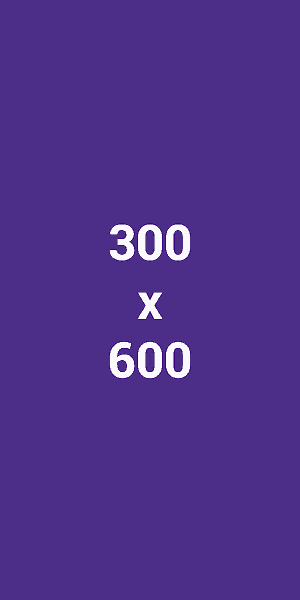



.jpg)

